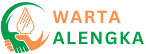|
| Sumber Foto: Kompas |
Selanjutnya,
Greatest Generation (1901–1927) lahir dan dibesarkan dalam bayang-bayang
Depresi Besar serta keterlibatan langsung dalam Perang Dunia II. Nilai
patriotisme, kerja keras, dan pengorbanan menjadi inti identitas mereka.
Generasi ini mewariskan etos disiplin tinggi dan solidaritas kolektif, diiringi
kemajuan teknologi awal seperti radio dan mesin industri yang mempercepat
urbanisasi.
Menyusul
setelahnya adalah Silent Generation (1928–1945) yang hidup dalam masa
pemulihan pascaperang dan awal Perang Dingin. Kehidupan mereka cenderung
konservatif, menghargai stabilitas, dan fokus pada pencapaian karier jangka
panjang. Meski mengalami kemajuan teknologi seperti televisi, mereka tumbuh
dalam norma sosial yang relatif ketat dan keterbatasan kebebasan berekspresi di
ruang publik.
Perubahan
besar muncul dengan hadirnya Baby Boomers (1946–1964), generasi yang
dibentuk oleh optimisme pascaperang, pertumbuhan ekonomi pesat, dan munculnya
budaya populer modern. Perkembangan televisi, musik rock, dan gerakan sosial
seperti hak-hak sipil dan feminisme memengaruhi pandangan hidup mereka.
Generasi ini dikenal ambisius, kompetitif, dan memiliki pengaruh besar dalam
lanskap politik serta ekonomi global.
Memasuki
Generation X (1965–1980), lahirlah kelompok yang mengalami peralihan
dari era analog ke digital awal. Mereka tumbuh di tengah meningkatnya angka
perceraian, globalisasi, dan munculnya komputer pribadi. Sifat independen,
adaptif, dan skeptis terhadap institusi menjadi ciri dominan. Generasi ini
menjadi penghubung penting antara pola kerja konvensional dan era teknologi
informasi modern.
Setelah
itu, Millennials atau Generation Y (1981–1996) muncul sebagai
generasi yang paling awal merasakan internet, ponsel, dan media sosial. Mereka
dibentuk oleh globalisasi, akses pendidikan lebih luas, dan nilai keberagaman.
Dengan karakter kolaboratif, melek teknologi, dan berorientasi pada pengalaman,
mereka juga menghadapi tantangan seperti krisis keuangan global 2008 dan
ketidakstabilan pasar kerja.
Lalu
hadir Generation Z (1997–2012), generasi digital native sejati yang
tidak pernah mengenal dunia tanpa internet. Teknologi, media sosial, dan
informasi instan membentuk pola pikir mereka yang serba cepat, kreatif, dan
sangat terhubung. Namun, mereka juga rentan terhadap tekanan mental akibat
paparan media yang berlebihan. Nilai inklusivitas, kesadaran lingkungan, dan
orientasi global menjadi ciri menonjol mereka.
Kini,
Generation Alpha (2013–2024) sedang tumbuh dalam lingkungan
hiper-digital dengan teknologi kecerdasan buatan, pembelajaran daring, dan
integrasi teknologi dalam hampir semua aspek kehidupan. Generasi ini
diperkirakan akan memiliki keterampilan adaptasi teknologi yang lebih tinggi,
tetapi juga tantangan dalam interaksi sosial tatap muka akibat ketergantungan
pada media digital.
Menyusul
setelahnya, Generation Beta (2025–2039) diprediksi lahir di tengah
percepatan revolusi teknologi seperti AI generatif, bioteknologi, dan sistem
transportasi otonom. Paparan awal terhadap ekosistem digital imersif, termasuk
realitas virtual dan augmented reality, dapat membentuk pola belajar yang lebih
visual, interaktif, dan personal. Namun, tingkat paparan terhadap perubahan
iklim, dinamika geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi global akan sangat
menentukan pembentukan nilai dan pola pikir generasi ini.
Perjalanan
dari Lost Generation hingga Generation Beta menunjukkan bahwa
setiap generasi merupakan hasil interaksi kompleks antara sejarah, budaya,
ekonomi, dan teknologi. Studi lintas generasi menjadi penting bukan hanya untuk
memahami perbedaan pola pikir, tetapi juga untuk merancang strategi pendidikan,
ekonomi, dan kebijakan publik yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan
masyarakat di masa depan. (WA/Ow)