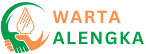|
Sumber Foto: Haluan Lifestyle |
WARTAALENGKA,
Cianjur –Dalam era yang ditandai oleh konektivitas tanpa batas,
justru semakin banyak individu yang secara sadar memilih untuk melakukan
perjalanan seorang diri. Fenomena ini dikenal sebagai solo traveling,
dan statistik global menunjukkan bahwa ini bukan sekadar tren musiman,
melainkan pergeseran gaya hidup yang signifikan.
Laporan
dari Statista (2024) menunjukkan peningkatan sebesar 42% dalam pencarian
kata kunci “solo travel” di mesin pencari global selama tiga tahun terakhir.
Platform pemesanan akomodasi seperti Booking.com dan Airbnb pun mencatat
lonjakan permintaan untuk penginapan satu orang. Fenomena ini tidak hanya
terjadi di negara-negara Barat, tetapi juga tumbuh pesat di Asia Tenggara,
termasuk Indonesia.
Alasan
di balik tren ini sangat kompleks dan tidak bisa dijelaskan secara sederhana.
Secara sosiologis, banyak orang—terutama dari kalangan Gen Z dan
milenial—menganggap perjalanan sendiri sebagai bentuk self-reclamation.
Dalam survei dari Solo Traveler Network (2023), 68% responden menyebut solo
traveling sebagai cara untuk “mengenal diri lebih dalam”, sementara 52% lainnya
menyebutnya sebagai “bentuk kebebasan absolut”.
Penelitian
dari University of Surrey (2022) menegaskan bahwa perjalanan seorang diri
memberi ruang bagi refleksi personal, pengambilan keputusan otonom, dan
peningkatan rasa percaya diri. Aspek ini tidak selalu tercapai dalam perjalanan
kelompok yang sering kali dikompromikan oleh keinginan kolektif.
Secara
psikologis, solo traveling juga memiliki manfaat terapeutik. Studi dari Journal
of Travel Research (2021) menemukan bahwa pelancong solo mengalami peningkatan
signifikan dalam indikator kesejahteraan psikologis, seperti emotional
resilience, problem-solving skill, dan empathy development.
Hal ini dipicu oleh seringnya mereka harus berinteraksi dengan orang asing,
memecahkan masalah sendiri, dan beradaptasi dalam lingkungan baru.
Namun,
tak sedikit pula yang memandang tren ini sebagai refleksi dari meningkatnya
kesepian sosial (social loneliness) di era digital. Studi dari
University of California (2023) menyoroti bahwa banyak orang muda memilih
bepergian sendiri karena merasa tidak memiliki jaringan sosial yang kuat untuk
berbagi pengalaman. Di sisi lain, ketergantungan pada teknologi menjadikan
mereka merasa “tidak sendirian” karena tetap terkoneksi dengan dunia maya.
Perempuan
menjadi kelompok dominan dalam tren ini. Menurut data dari Hostelworld (2023),
63% solo traveler adalah perempuan, dan mayoritas dari mereka melaporkan
peningkatan rasa empowerment setelah melakukan perjalanan sendiri. Ini
menjadi indikator penting bahwa solo traveling tidak lagi diasosiasikan dengan
risiko, melainkan dengan self-liberation.
Dari
sisi ekonomi, industri pariwisata mulai merespons fenomena ini dengan
menyediakan lebih banyak opsi individual-friendly: kamar tunggal, itinerary
fleksibel, dan destinasi yang ramah untuk pelancong solo. Negara seperti
Jepang, Islandia, dan Portugal bahkan mempromosikan diri sebagai “surga bagi
solo traveler”.
Namun,
bukan berarti tanpa risiko. Keamanan menjadi isu utama. Data dari Global Peace
Index (2023) menunjukkan bahwa pelancong tunggal lebih rentan terhadap tindak
kejahatan, terutama di negara dengan indeks keamanan rendah. Oleh karena itu,
edukasi dan perencanaan menjadi aspek krusial sebelum memulai perjalanan solo.
Di
sisi budaya, masyarakat urban modern mulai melihat solo traveling sebagai
bentuk prestise sosial. Media sosial berperan besar dalam hal ini.
Gambar-gambar puitis tentang seseorang yang menatap matahari terbenam di
Santorini atau membaca buku di café tersembunyi Kyoto menjadi simbol gaya hidup
mindful dan mandiri.
Akan
tetapi, tren ini juga menghadirkan paradoks. Di tengah glorifikasi kebebasan
individu, apakah kita secara tidak sadar sedang menormalisasi keterasingan
sosial? Apakah solo traveling benar-benar bentuk kemandirian, atau justru
eskapisme dari dunia yang terlalu bising dan kompleks?
Sejumlah
pakar menyarankan pendekatan kritis. Dr. Laura Bianchi dari University of
Amsterdam mengingatkan bahwa solo traveling sebaiknya dipahami sebagai proses intentional
solitude yang sehat, bukan sekadar pelarian dari relasi sosial yang gagal.
Dalam
konteks pendidikan karakter, perjalanan seorang diri dapat menjadi ruang
pembelajaran hidup yang autentik. Anak muda belajar disiplin, toleransi,
adaptasi, dan tanggung jawab melalui pengalaman nyata, bukan dari teori atau
seminar motivasi.
Kesimpulannya,
solo traveling bukan lagi subkultur marginal, tetapi telah menjadi
ekspresi gaya hidup modern yang sarat makna. Ia bisa menjadi sarana penguatan
diri, tetapi juga bisa mencerminkan kekosongan relasi sosial. Maka yang paling
penting bukan pada status “sendirian atau tidak”, melainkan pada kesadaran
mengapa seseorang memilih untuk sendiri. (WA/Ow)