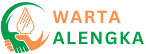|
| Sumber Foto: Istimewa |
WARTAALENGKA,
Cianjur – Fenomena viral “Rp10.000 di tangan istri yang tepat”
menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama TikTok dan Instagram.
Sekilas, narasi ini terdengar romantis dan menggugah, menampilkan sosok istri
yang hemat, cerdas, dan penuh kasih dalam mengelola keuangan keluarga. Namun,
di balik pesan manis itu tersimpan persoalan serius yang berkaitan dengan kesenjangan
ekonomi, ketimpangan gender, dan bentuk kekerasan ekonomi yang dinormalisasi
dalam masyarakat patriarkal.
Dari
perspektif sosiologi, fenomena ini dapat dikaji melalui teori gender role
socialization yang dikemukakan oleh Eagly & Wood (2012), di mana
masyarakat membentuk ekspektasi berbeda terhadap peran laki-laki dan perempuan.
Laki-laki sering diasosiasikan dengan pencari nafkah utama, sedangkan perempuan
diposisikan sebagai pengatur rumah tangga. Dalam struktur ini, ketika ekonomi
keluarga lemah, tanggung jawab finansial justru sering bergeser ke pundak
perempuan — bukan sebagai pencari pendapatan utama, tetapi sebagai “penyelamat”
yang harus menyulap kekurangan menjadi kecukupan.
Secara
ekonomi, narasi “Rp10.000 di tangan istri yang tepat” mencerminkan fenomena
ketahanan rumah tangga berpendapatan rendah, di mana perempuan memainkan peran
strategis dalam manajemen keuangan mikro. Penelitian oleh Asian Development
Bank (2021) menemukan bahwa 68% rumah tangga di Indonesia bergantung pada
keterampilan perempuan dalam mengatur keuangan untuk bertahan hidup, terutama
di sektor informal. Namun, kemampuan ini sering dipuji bukan sebagai bentuk
pemberdayaan, melainkan sebagai bukti “istri baik” yang bisa berhemat dalam
keterbatasan.
Dari
sisi psikologi sosial, romantisasi terhadap perempuan hemat justru menciptakan
tekanan emosional dan beban mental ganda. Perempuan dihadapkan pada dilema
antara ideal sosial sebagai istri yang “setia dan sabar” dengan realitas
psikologis berupa stres, rasa bersalah, dan kelelahan mental akibat tanggung
jawab ekonomi yang tak proporsional. American Psychological Association
(APA, 2020) mencatat bahwa ketimpangan peran dalam pengelolaan ekonomi
rumah tangga menjadi salah satu faktor utama pemicu stres dan konflik
perkawinan.
Fenomena
ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan ekonomi terselubung
(financial abuse). Menurut UN Women (2022), kekerasan ekonomi adalah
bentuk kontrol terhadap sumber daya finansial yang membuat satu pihak (biasanya
perempuan) bergantung secara ekonomi pada pasangan, sehingga kehilangan otonomi
dan daya tawar dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, narasi “istri
yang baik bisa mengatur uang berapa pun” justru memperkuat legitimasi atas
minimnya tanggung jawab finansial dari pihak suami.
Lebih
jauh, tren ini memperlihatkan bagaimana media sosial berperan dalam memperkuat
konstruksi budaya patriarkal. Melalui meme, video pendek, dan
narasi romantik, muncul glorifikasi terhadap penderitaan perempuan. Konsep
seperti “istri hebat itu yang bisa diajak susah” dipopulerkan, padahal secara
struktural justru memperpanjang ketimpangan dan mengaburkan urgensi keadilan
ekonomi dalam rumah tangga. Ini sejalan dengan konsep symbolic violence
yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, yakni bentuk dominasi halus yang
diterima tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan.
Dalam
banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang harus “berkreasi” agar rumah tangga
tetap berjalan, seperti menjual makanan kecil, menjadi reseller, atau mencari
penghasilan tambahan, sementara suami tidak mengalami tekanan sosial serupa. Komnas
Perempuan (2023) mencatat bahwa 31% kasus kekerasan domestik di Indonesia
memiliki unsur kekerasan ekonomi — mulai dari penelantaran finansial hingga
pembatasan akses terhadap uang.
Dari
sisi komunikasi dan budaya, tren seperti ini juga memperlihatkan bagaimana
narasi digital dapat membentuk opini publik. Social media discourse analysis
yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (2024) menemukan bahwa 73%
konten viral bertema “istri hebat hemat” memiliki nada romantisasi, bukan
edukasi. Hal ini menandakan bahwa media sosial tidak hanya merefleksikan budaya
patriarkal, tetapi juga memperkuatnya melalui humor, konten “relate”, dan framing
emosional.
Dampaknya
tidak kecil. Banyak perempuan mulai menormalisasi kesulitan ekonomi dan
menjadikannya sebagai bentuk cinta atau pengabdian. Padahal, menurut perspektif
psychological empowerment theory (Zimmerman, 1995), kesejahteraan
emosional dan finansial seseorang sangat bergantung pada rasa kontrol terhadap
hidupnya sendiri. Ketika perempuan kehilangan akses dan otonomi finansial, maka
hilang pula sebagian kendali terhadap kesejahteraannya.
Namun,
bukan berarti narasi ini sepenuhnya negatif. Di satu sisi, ia menunjukkan
kekuatan perempuan dalam bertahan dan beradaptasi. Akan tetapi, kekuatan ini
tidak boleh dijadikan pembenaran atas ketimpangan struktural. Sebagaimana
diungkapkan oleh bell hooks (2000) dalam teorinya tentang feminist
love ethics, cinta sejati dalam relasi bukanlah pengorbanan sepihak,
melainkan kolaborasi yang adil dan saling menghargai peran.
Secara
sosial, langkah korektif perlu dilakukan melalui dua arah: pendidikan ekonomi
rumah tangga dan rekonstruksi budaya populer. Literasi finansial pasangan suami
istri perlu diperkuat agar perencanaan keuangan tidak menjadi beban satu pihak.
Selain itu, media massa dan kreator konten juga memiliki tanggung jawab moral
untuk tidak menormalisasi narasi romantisasi kemiskinan yang mengorbankan
perempuan.
Kesimpulannya,
tren “Rp10.000 di tangan istri yang tepat” bukan sekadar konten viral,
melainkan cermin dari realitas sosial yang kompleks. Ia menggambarkan
ketimpangan peran ekonomi dalam rumah tangga dan sekaligus menyoroti betapa
mudahnya kekerasan ekonomi disamarkan di balik romantisme. Di era digital, kesadaran
kritis terhadap pesan semacam ini menjadi penting — bukan hanya untuk membela
perempuan, tapi untuk membangun relasi yang sehat, setara, dan manusiawi di
tengah tekanan sosial dan ekonomi yang kian nyata. (WA/Ow)